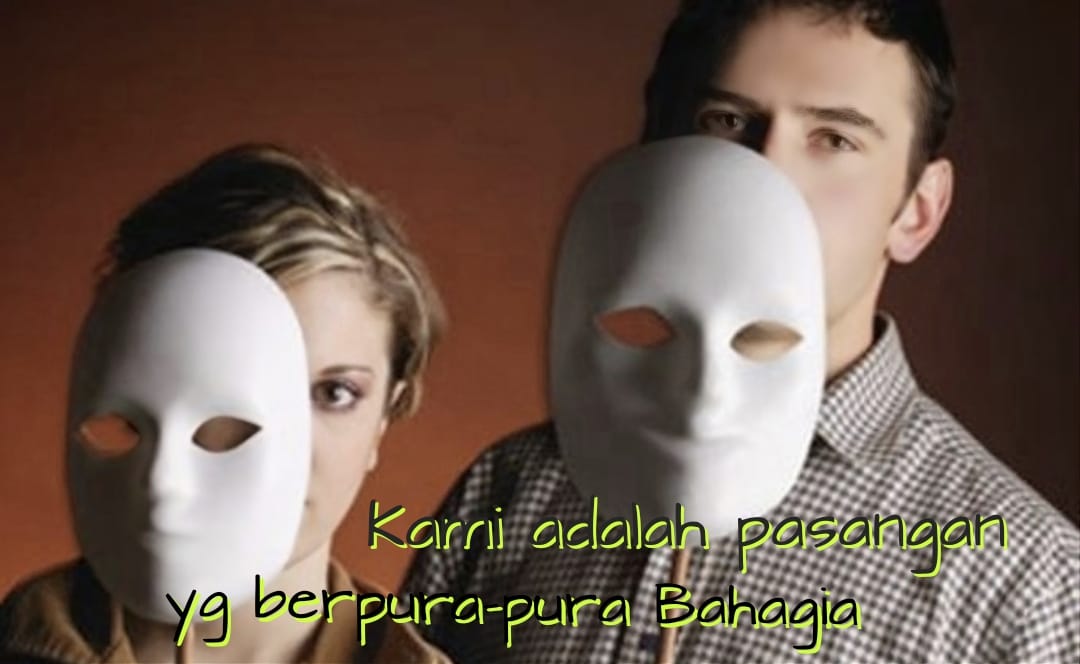(Nama dalam cerita ini telah di samarkan)
Tak salah menjadi seseorang yang selalu terlihat bahagia untuk menegaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di titik tertentu, itu bisa jadi petaka.
Saya adalah bukti nyatanya. Gara-gara terlalu sering berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, saya nyaris bercerai.
Proses perceraian itu sungguh melelahkan. Ia ibarat tercebur di tengah lautan. Energi pelan-pelan habis karena kau harus berenang ke tepian bertemu tujuan.
Beberapa hari sebelum jadwal sidang perceraian yang pertama, saya kehabisan akal. Rasa gundah yang tak tertolong membuat saya kabur dari jam kerja, berlari menuju mobil, dan melaju kencang menuju rumah. Hanya ingin menyampaikan satu kalimat pada istri di rumah: “Aku enggak mau bercerai”.
“Aku minta waktu, ya,” ujar Rani, perempuan yang kala itu telah lima tahun mendampingi saya.
Di hari persidangan, Rani tak datang. Bagi saya, itu adalah jawaban setuju untuk rujuk.
Satu dekade lalu, Rani adalah perempuan impian. Dia menjadi representasi perempuan ideal di kampus: cantik, pintar, baik, tempat curhat yang enak, dan mandiri. Begitu pula dengan saya, dikenal sebagai mahasiswa yang selalu akrab dengan siapa pun.
Jika didefinisikan, hubungan kami adalah hubungan yang diinginkan society. Hubungan kami kerap dielu-elukan, dianggap sebagai pasangan yang sempurna.
Tak boleh ada cacat yang terlihat. Jika kami terlihat bertengkar, orang-orang menegur.
“Ngapain, sih, pakai berantem segala? Rani, tuh, kurang apa? Baikan aja lah.” Begitu kira-kira orang berkata saat itu.
Dari sana, tanpa disadari kami beradaptasi dengan ekspektasi orang lain, bukan keinginan kami sendiri. Kami pun terus berusaha terlihat sempurna di depan orang-orang.
Keretakan hubungan sebenarnya telah tercium sejak kami masih berpacaran. Ekspektasi orang diam-diam membuat saya muak.
Ekspektasi adalah musuh manusia. Ekspektasi tak lebih dari harapan yang disimpan secara berlebihan.
Beberapa kali saya mencoba berselingkuh.
Bukan apa-apa, dengan perempuan lain, saya menjadi diri sendiri dan bisa melakukan apa pun yang saya inginkan. Tapi tidak dengan Rani.
Sampai akhirnya dorongan untuk menikah pun muncul.
Bagi kami, yang kala itu telah berpacaran selama enam tahun, pernikahan ibarat sebuah kewajiban. Karena pernikahan kami-lah yang diinginkan banyak orang.
“Ngapain, sih, pacaran enam tahun enggak nikah-nikah?” Kira-kira begitu pendapat banyak orang. Pernikahan seperti bagian dari sistem yang harus saya dan Rani tempuh.
Tanpa sadar, kebiasaan untuk memenuhi ekspektasi orang lain dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja terbawa hingga kehidupan rumah tangga.
Rasa lelah, tekanan mental karena kerja, berbagai beban pikiran tak pernah saya bagi dengan Rani. Saya biarkan Rani berhadapan dengan suaminya yang selalu ceria dan hangat. Saya selalu mencoba tersenyum, meski hati terasa lelah.
Puncaknya terjadi setelah Rani melahirkan buah hati kami. Rani berubah menjadi sosok yang berbeda. Tak ada sedikit pun rona kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya.
Tapi lagi-lagi, kami selalu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Rani tak bercerita tentang perasaannya, begitu pula saya yang selalu bersikap seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan.
Selama 1,5 tahun setelah melahirkan, saya bahkan tak bisa menyentuhnya. Jangankan bersetubuh, memeluk atau menciumnya pun sulit. Rani menutup akses tanpa kata-kata dan aba-aba.
Suatu hari kami mencoba kembali berhubungan fisik. Di tengah-tengah adegan ranjang yang rasanya begitu menggelora, mulutnya bergumam dan bersuara, “Ck..”. Gumaman itu seolah menggambarkan perasaan malas, enggan, dan tak suka.
Rasanya ingin marah. Sebagai pria, saya merasa direndahkan.
Tapi kembali lagi, saya tetap mencoba berpura-pura tak masalah. Saya bahkan harus pura-pura orgasme demi mempercepat aksi ranjang.
Buntutnya, saya tak pernah lagi bisa ereksi saat mencoba mencumbunya.
Hasil konseling dengan psikolog saat proses perceraian berlangsung, saya mengalami sedikit trauma.
Sampai saat ini bahkan gumaman itu masih terus terngiang di telinga. Gumaman itu tanpa sadar membuat saya membenci dan tak bisa memaafkan Rani, meski di depannya saya selalu terlihat hangat dan bahagia.
Alih-alih mengutarakan perasaan pada Rani, saya memilih untuk kembali berselingkuh. Anehnya, dengan perempuan lain, saya bisa ereksi. Tapi tak bisa jika bersama Rani.
Dari sana, tanduk iblis seolah langsung tumbuh di kepala. Selama dua tahun, saya berselingkuh dengan beberapa perempuan lain.
Rasanya sedih, tapi juga senang. Sedih karena berselingkuh dan merasa bersalah pada anak, tapi senang karena ternyata saya masih lelaki ‘normal’.
Rasa sayang pada Rani juga perlahan hilang, atau mungkin bersembunyi?
Tapi perlahan rasanya lelah juga. Berpura-pura baik-baik saja di depan Rani, sambil juga menyembunyikan kisah-kisah asmara saya bersama perempuan lain. Saya memilih untuk jujur dan mengakui apa yang saya lakukan.
Jawabannya jelas, Rani langsung minta berpisah.
Dari sana hingga akhirnya Rani resmi melayangkan gugatan cerai, kira-kira selama satu tahun, pertengkaran jadi makanan sehari-hari. Selalu ada hal yang kami ributkan. Melelahkan.
Beberapa kali bahkan Nadia, anak kami, melihat pertengkaran orang tuanya. Hal ini yang sampai sekarang membuat saya masih terus merasa bersalah.
Talak satu usai, berlanjut ke talak dua. Kami berpisah rumah selama tiga bulan. Tapi rasanya melelahkan.
Sebisa mungkin, kami berusaha agar Nadia tak tahu bahwa kami tinggal di atap yang berbeda. Setiap pulang kantor, saya pulang ke rumah untuk menina-bobokan Nadia, berpura-pura mau tidur. Lalu pulang ke apartemen, dan keesokan paginya kembali ke rumah, berpura-pura seolah ayahnya sudah terbangun dan menemaninya bermain.
Hopeless, beberapa kali saya dan Rani bertemu untuk membicarakan Nadia. Merencanakan kehidupan Nadia saat nanti kami resmi berpisah.
Tapi, diam-diam pertemuan itu menyalakan kembali getar-getar kehangatan di antara kami. Saya sadar, selama ini yang ada di kepala hanyalah keluhan demi keluhan, tapi saya lupa cerita-cerita manis yang pernah ada di baliknya.
Lucunya, saat kabar soal rencana perceraian kami tersebar, banyak teman yang menghubungi. Ternyata, banyak orang di sekeliling saya yang mengalami hal serupa: mau bercerai, hampir bercerai, atau bahkan sudah bercerai.
Rata-rata masalahnya berawal dari ekspektasi orang lain, meski dengan problematika yang berbeda. Dari sana saya berpikir, ternyata banyak orang yang berusaha menjadi seperti apa yang diinginkan orang lain. Lagi-lagi, mereka berpura-pura.
Saya yakin, masalah seperti ini terjadi di banyak rumah tangga. Ada yang sadar untuk bergerak memperbaiki, ada yang sadar sampai bercerai, ada juga yang tak sadar dan hanya mencoba menjalaninya.
Kini, saya dan Rani tengah sama-sama mencoba belajar dan memperbaiki diri, meski susahnya minta ampun.
Tak perlu lagi berpura-pura, baik satu sama lain atau pada orang lain. Kami mencoba untuk lebih saling terbuka tanpa perlu memikirkan apa yang diinginkan orang lain.
Kami juga tak mau lagi berusaha memenuhi ekspektasi publik. Jika bertengkar, ya, bertengkar saja. Jika kejadian serupa kembali terulang dan kami harus bercerai, saya ikhlas, biarkan saja itu terjadi.
Toh, kami sudah berusaha. Perceraian atau keretakan rumah tangga juga bukanlah sebuah kesalahan. Lagi pula, apa salahnya untuk menjadi tidak sempurna?
ℹ️ Artikel telah tayang pada rubrik CNN Indonesia 16 Okt 2022.